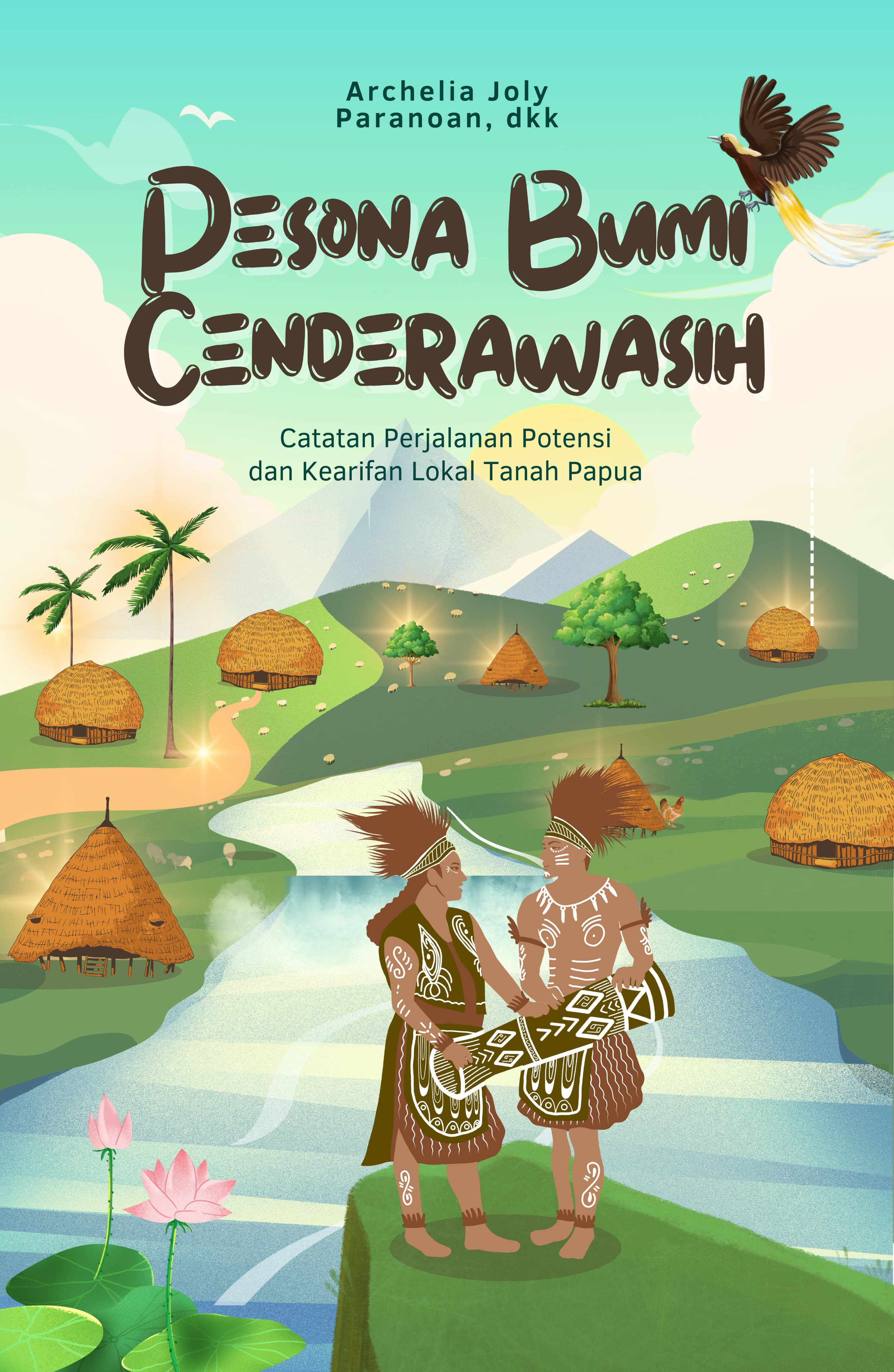
Bakar Batu
Dering alarm membangunkanku pagi itu. Dengan nyawa setengah sadar, ku raih ponselku untuk melihat pukul berapa ini? Aku loncat dari ranjang hotel saat tahu pukul menunjukan 10.45 WIT. Harusnya aku ada janji dengan temanku, Francisco. Dia seorang pemandu wisata yang kutemui saat hendak menuju hotel dari bandara. Banyak hal baru yang aku dapat darinya yang kini menjadi temanku. Tapi, ada satu hal yang membuatku sangat tertarik padanya. Ini tentang suatu tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Bakar Batu.
“Francisco!”
Teriakku di depan pintu kafetaria hotel.
“Hei Teman! Mari duduk sini.”
Ucapnya mempersilahkan aku duduk di sampingnya.
“kenapa ko baru datang? Sa su tunggu dari pagi. Tong dua baku janji jam 8 baru.”
Protes Francisco dengan sedikit kekehan kecil diwajahnya.
“Aduh, maaf kawan saya terlambat bangun. Jadi? Kita hari ini mau bikin apa saja? Bagaimana tentang yang kemarin kamu bilang? Eee... tentang tradisi bakar batu! Sebenarnya itu apa? bisa kamu jelaskan dulu?”
Balasku dengan aksen medok khas Jawa yang sedikit aku paksa ke timur-timuran.
“Oh... sebenarnya bakar batu itu tradisi turun temurun dari tong punya nenek moyang begitu. Jadi kitorang masak makanan di atas batu yang dipanaskan menggunakan api.”
Jelasnya sembari melihat ke arah kiri atas seperti mencoba mengingat sesuatu.
“Kenapa harus batu?”
Tanyaku penasaran.
“Karna dulu ketersediaan batu itu melimpah sekali di sini, di Papua. Dan juga, batu ini bisa menyimpan panas dengan baik.”
Jawabnya dengan penuh rasa bangga.
“Oh.. begitu. Lalu, kita bisa melihat tradisi ini di mana?”
Aku kembali bertanya.
“Biasanya dilakukan oleh suku-suku pedalaman seperti Nabire, Lembah Baliem, Paniai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Dekai. Tapi, di kota macam Jayapura ini juga ko su bisa lihat tradisi bakar batu. Kebetulan hari ini sa mau ajak ko ke Kampung Asei. Salah satu kapung adat yang terkenal dengan tradisi bakar batu.”
Ajak Francisco dengan ramah.
Dengan semangat aku menerima ajakannya dan ku anggukan kepala sebagai tanda setuju. Panas matahari menembus kulit. Suhu hari ini mencapai 39° Celcius. Aku dan Francisco berjalan kaki menuju rumahnya. Jaraknya tidak terlalu jauh dari hotel Swiss-bell tempatku menginap. Sekitar dua puluh menit kami mengendarai sepeda motor, akhirnya kami sampai di sebuah kampung adat yang terletak di dekat Danau Sentani. Suasananya sangat ramai. Banyak anak kecil berlalu lalang menarik mobil truk mainan mereka yang bertali rapia. Suasana ini sangat baru untukku.
“Nah teman, hari ini sa ade sepupu ulang tahun yang ke-17 jadi tong semua rayakan dengan makan-makan. Makanan yang tong makan itu, dimasak dengan metode bakar batu.”
Ucap Francisco sembari berjalan melangkahkan kakinya memasuki pintu rumah.
“Mama... sa datang bawa teman ini!”
Aku tersenyum lalu menyalami seorang wanita di depanku yang dipanggilnya Mama.
“Nama saya agus, bu”
“Jangan panggil “Bu”. Panggil saja “Mama”, itu sebutan untuk perempuan yang lebih tua.”
Senyum penuh tawa tercetak jelas di wajahnya.
Terlalu lama aku terhanyut dalam suasana gembira dan hangat ini sampai tak terasa adzan maghrib berkumandang.
“Agus, ko tra pergi ibadah kah? Sudah bunyi masjid ini.”
Lama aku mengolah kalimat “Sudah bunyi masjid”. Rupanya yang Francisco maksud adalah suara adzan maghrib.
“Saya baru mau tanya. Apa ada masjid di dekat sini?”
Tanyaku kepada Francisco.
“Tentu saja ada! Ko bisa ibadah di Masjid Al-Aqsa yang besar itu.”
Kuanggukan leherku dan berjalan menuju masjid tersebut.
Setelah sekitar 30 menit aku pergi, aku kembali ke Kampung Asei. Aku dihadapkan dengan sekumpulan orang yang sedang berbincang dan makanan yang diletakkan disebuah tumpukan batu. Ahh.. bakar batu.
“Eh teman, sini kita duduk cerita-cerita!”
Ajak Francisco kepadaku.
Akupun duduk tepat disebelah Francisco. Di sebelahnya lagi ada seorang bapak-bapak paruh baya yang usianya mungkin setengah abad lebih, sepertinya dia adalah ketua adat di kampung ini. Aku banyak bertanya kepadanya. Beliau menjawab dengan sangat ramah dan mudah dimengerti.
“Jadi, kalau dalam bahasa kami itu namanya “Mambule”. Ini merupakan tradisi yang sudah ada dari zaman prasejarah. Teknik memasaknya sangat mudah tapi butuh keahlian khusus. Ade ada lihat batu-batu itu? Sebelum diletakkan makanan di atasnya, batu itu dipanaskan dulu dengan api. Baru diletakkan makanan yang sudah dibungkus dengan daun pisang atau kelapa. Kalau sudah ditutupi lagi dengan daun kering supaya dia punya panas tetap terjaga.”
Jelas lelaki paruh baya itu dengan nada bicara yang berwibawa.
“Sebenarnya bakar batu itu bukan hanya metode memasak. Tapi jadi lambang simbolis dalam masyarakat Papua, Agus. Begitu toh bapak?”
Tambah Agus kepada bapak tersebut.
“Betul sekali, dalam masyarakat Papua, bakar batu tidak hanya menjadi cara memasak. Tetapi juga menjadi suatu simbolis yang melambangkan kebersamaan, kekeluargaan, serta rasa syukur kita terhadap Tuhan. Makanya sering dijumpai saat upacara adat, pernikahan, kematian, acara ucapan syukur yang kitorang ada bikin sekarang ini juga.”
Lanjut lelaki itu.
“Tapi bapak, cuma makanan kering saja kah yang bisa dimasak seperti ikan, daging, sayuran, atau umbi-umbian?”
Tanyaku penuh rasa penasaran yang mulai hanyut terbawa suasana.
“Tidak juga. Ade su pernah makan papeda? Itu juga bisa dimasak dengan cara bakar batu. Jadi, prosesnya itu kita masukan air ke dalam loyang yang berisi sagu, lalu dimasak di atas batu yang sudah dipanaskan. Kalau sudah, kita aduk pakai sendok kayu sampai teksturnya mengental. Jadi bukan cuma makanan kering saja, makanan berkuah juga bisa. Kue juga bisa, macam kue saksak yang terbuat dari sagu.”
Jawab bapak dengan senyuman tipis menghiasi wajahnya.
Tak terasa waktu menunjukan pukul 23.32 yang artinya sudah sangat lama aku berjalan-jalan. Aku memutuskan untuk pulang ke hotel, bersama teman sekaligus pemandu wisataku yang memberikan banyak hal yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya.
“Bagaimana? Seru kah tidak ikut acara bakar batu macam tadi?”
Ucap Francisco memecah keheningan.
“Seru banget! Banyak hal yang bisa aku jadikan pengalaman. Jika pulang ke Solo nanti, aku akan bercerita tentang hari ini kepada semua orang, agar budaya Papua semakin dikenal banyak orang! Siapa tau bisa membuka kesempatan dikenal di panggung global.”
Jawabku dengan semangat.
“Baguslah kalau ko merasa senang. Semoga generasi muda Papua bisa terus menjaga tradisi ini. Kalau begitu sa pulang dulu, senang bisa kenal dengan ko, Agus.”
Francisco berjalan meninggalkanku di tepas hotel. Aku kembali masuk ke kamarku dan membuka laptop, mengetik sebuah judul di halaman blogku, yaitu “Bakar Batu”. Menuangkan segala kehebatan yang aku rasakan hari ini.
